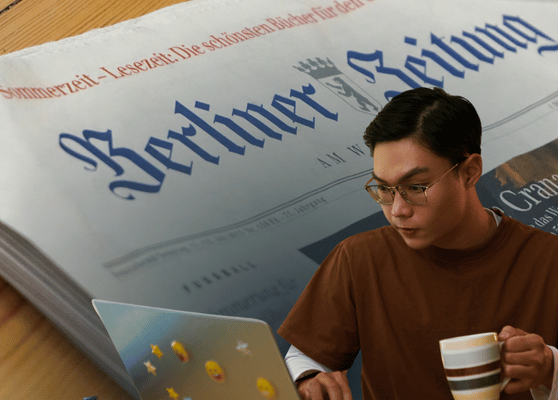Media Massa dan “Overdosis” Liputan Terorisme
–Merlina Maria Barbara Apul
Teroris Jancuuk!! Begitu ekspresi kemarahan warga Surabaya yang terwujud dalam sejumlah baliho yang terpasang di beberapa sudut Kota Pahlawan, pasca aksi bom bunuh diri satu keluarga di tiga gereja pada 13 Mei 2018 dan serangan bom kendaraan yang menimpa Mapolrestabes Surabaya ke-esokan harinya (Tempo.co, 2018). Image kota Surabaya yang selama ini jauh dari isu terorisme membuat sejumlah media baik cetak, elektronik hingga online selama 24 jam non-stop meliput aksi terorisme ini. Baik media cetak skala nasional hingga lokal menempatkan kejadian ini sebagai headline news di halaman utama, sedangkan media elektronik menjadikan aksi para teroris ini sebagai breaking news. Di sisi lain, detik demi detik peristiwa tersebut dilaporkan secara terperinci dan cepat di media daring sehingga langsung dikonsumsi publik dalam waktu sekejap. Terlebih, latar belakang pelaku teroris yang merupakan satu keluarga dan seorang anak perempuan yang sempat diselamatkan polisi ketika mengikuti aksi orang tuanya dalam bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya, bagaikan koreografi drama, skenario teatrikal semacam ini sangat ampuh untuk menarik perhatian media massa guna mempublikasikannya secara gegap gempita.
Modus baru para teroris ini pada akhirnya sukses menebar ancaman ketakutan tidak hanya bagi warga Surabaya namun meluas di sejumlah wilayah Indonesia khususnya pengamanan gereja dan kantor polisi yang diperketat. Dengan kata lain, melalui liputan intensif media massa, tujuan teroris untuk mengeksploitasi aspek psikologis masyarakat dengan rasa takut berhasil dilakukan. Fenomena ini dikatakan Behm (dalam Nunung, 2004: 37-38) memunculkan gugatan terhadap keberadaan media massa dalam aktivitas menentang terorisme. Behm menyebut, sejatinya media massa dan teroris memiliki kepentingan yang sama. Dalam konteks ini, teroris menyusun dan memanfaatkan media massa untuk memperluas pengaruh mereka dan disaat yang sama, media menempatkan kepentingannya pada aktivitas kelompok teroris. Bagi Behm, relasi “simbiosis-mutualisme” demikian, membuat terorisme tak boleh hanya dipandang sebagai tindakan kekerasan semata, melainkan merupakan wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan.
Asumsi ini diperkuat oleh pengakuan Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda saat ini, yang mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan sebuah pertempuran, dan lebih dari setengah pertempuran ini berada di ranah media. Pertarungan media ini mereka lakukan untuk merebut hati dan pikiran umat (Seib dan Janbek, 2011). Pernyataan ini menjadi indikasi besar bahwa para teroris telah menyadari peranan media sehingga memasukkan aspek media ke dalam strategi teror mereka. Menurut Brigitte Nacos (2002), keberhasilan aksi terorisme memang seringkali bisa diukur dari luas dan intensifnya peliputan media yang mereka dapatkan. Namun ia juga berpendapat bahwa anggapan ini terlalu simplistik dan meluputkan kompleksitas terorisme dan media itu sendiri. Nacos merumuskan tujuan terorisme menjadi tiga lingkup utama: mendapat perhatian, pengakuan, dan rasa hormat pada taraf terentu. Ketiga hal tersebut bisa dicapai tanpa unsur kekerasan, maka Nacos menganggap pasti ada aspek khusus yang mengaitkan kekerasan pada hubungan terorisme dengan media.
(Sumber gambar: ec.europa.eu)
Melihat hubungan aksi terorisme dengan liputan media, menurut Soriano (dalam Imaduddin, 2016) perlu menyelami logika media, khususnya televisi. Media televisi yang sangat mengandalkan aspek visual dan sensasionalisme dalam menentukan nilai berita menjadi “senjata” ampuh bagi para teroris. Aksi bom bunuh diri yang tidak lagi menjadi aksi perseorangan melainkan melibatkan satu keluarga dan munculnya perempuan serta anak-anak sebagai pelaku bom, amat sejalan dengan logika televisi yang menaruh nilai besar pada unsur “kebaruan” (novelty) kisah yang bisa diangkat. Sementara aspek visual dan sensasional dapat dilihat ketika bom Sarinah terjadi. Berbeda dengan Bom Bali yang memakan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang jauh lebih besar, Bom Sarinah menurut Imaduddin dilakukan pihak teroris dengan lebih memperhitungkan pola kerja media. Lokasi Sarinah dijantung kota serta dekat dengan pusat pemerintahan dan perwakilan negara-negara, juga pusat konsumerisme dan gaya hidup modern yang dianggap sebagai simbol barat, memudahkan media untuk segera melakukan peliputan dengan cepat. Kombinasi serangan bom dengan aksi baku tembak pelaku teror dan aparat membuat media dapat melakukan peliputan dalam tempo waktu berjam-jam, menghipnotis masyarakat untuk terpaku pada layar televisi. Bagi Imaduddin, serangan Sarinah bekerja dengan cara yang lebih mirip showmanship panggung sulap dari pada medan perang. Fokus serangan mereka adalah peliputan media bukan kerusakan fisik atau target korban jiwa berjumlah besar.
“Overdosis-nya” liputan media terhadap aktivitas terorisme tanpa disadari menjadi motivasi bagi rekan sesama teroris untuk meningkatkan aksi mereka. Safril (2016) mengatakan, publikasi media selain bertujuan menebarkan ketakutan juga dimaksudkan sebagai pesan terselubung kepada jaringan lain agar ikut bergerak melawan musuh. Karena itu, setiap peristiwa terorisme hampir pasti diikuti aksi-aksi teror lainnya. Realitas itulah yang terjadi ketika dua hari setelah bom Surabaya, Polda Riau menjadi korban aksi teror, diikuti sejumlah penggrebekan hingga baku tembak dengan terduga teroris. Dengan begitu, kian tampak eksistensi kelompok teroris sejatinya masih terjaga meskipun telah banyak anggotanya yang tewas atau tertangkap.
Logika media yang demikian akan membuat terorisme selalu menjadi perhatian utama media massa dalam peliputannya. Meminjam pemikiran Walter Laqueur (2004), yang mengatakan “the media are the terrorist’s best friends. The terrorist’s act by itself is nothing, publicity is all” yang berarti sebagai sahabat baik, keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan masing-masing dengan tujuan berbeda. Mendalami permasalahan ini, menurut Chaudhary (dalam Nunung, 2004) media perlu bertanggung jawab mewartakan peristiwa terorisme dengan menekankan objetivitas yang terkait dengan akurasi, fakta, kesimbangan dan cara pandang tak bias yang harus diikuti kebijakan apa saja fakta yang harus dilaporkan, diabaikan atau bahkan dilupakan secara total demi kepentingan publik.
Nunung menambahkan, berfokusnya media pada aktivitas terorisme menyebabkan media kurang sensitif terhadap kerugian sosial dan solusi terhadap persoalan terorisme banyak terpinggirkan dalam wacana media massa.
Mencermati realitas “saling mendukung” antara media massa dan terorisme untuk mencapai kepentingan masing-masing, solusi seperti kebijakan sensor terhadap aksi teror tampaknya terlalu naif, mengingat di era konvergensi media dan kuatnya pengaruh media sosial, membuat aksi kekerasan seperti terorisme akan mudah tersebar dan sulit disembunyikan dari masyarakat. Menyembunyikan fakta pun tidak akan menyebabkan suatu kejadian buruk menghilang, dan masyarakat berhak tahu atas segala potensi ancaman yang bisa terjadi. Agar media massa terhindar dari “anarki pasar” dalam meliput terorisme, meminjam pemikiran Jetter (2014), media perlu membahas isu teror dengan orientasi memandu masyarakat dalam menyikapi ancaman dengan baik, atau bahkan membantu masyarakat secara aktif ikut berkontribusi dalam menghadapi isu dan potensi teror. Jangan sampai media memberi apa yang paling teroris inginkan: perhatian dan wadah untuk menyampaikan pesan.
Merlina Maria Barbara Apul merupakan Awardee LPDP yang sedang menempuh studi di Magister Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM.